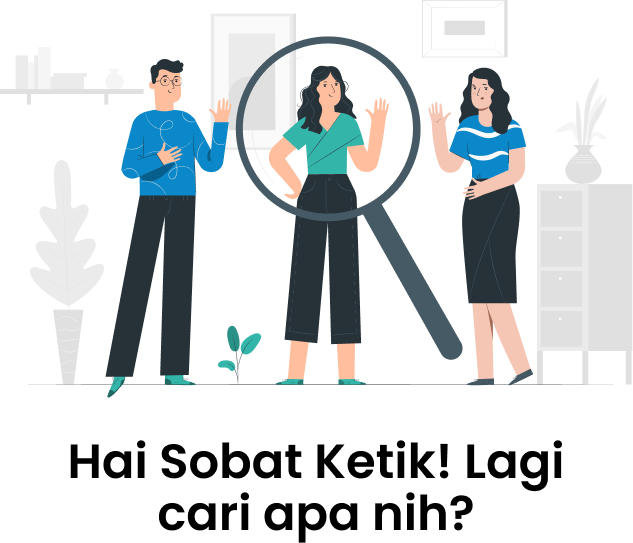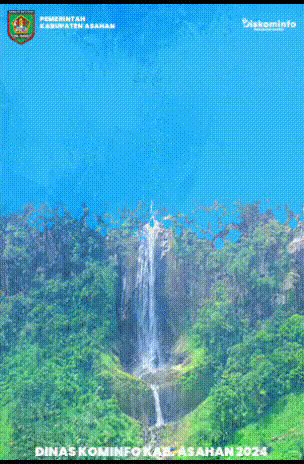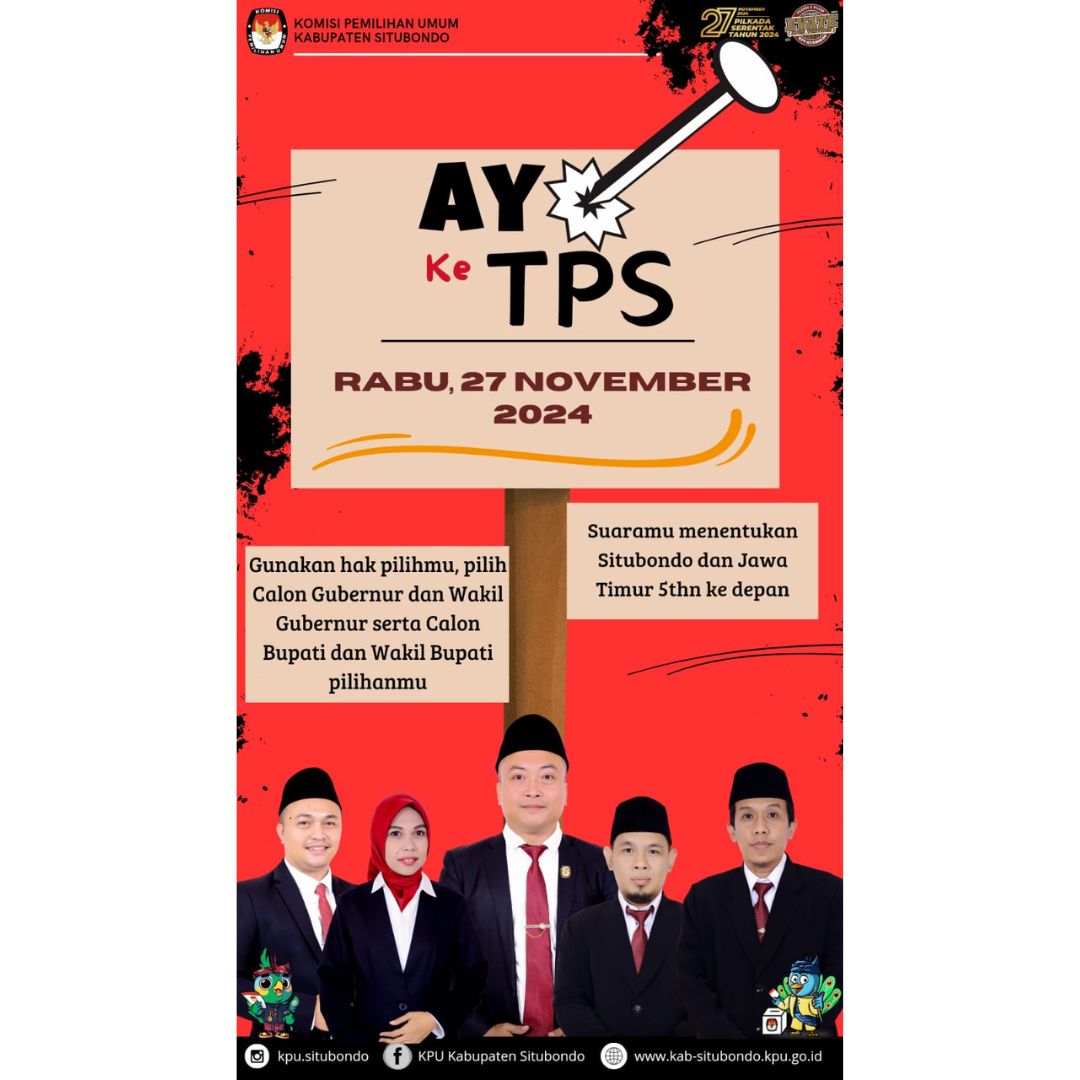Dalam sunyi sel tahanan, detik jam berdetak monoton seperti menghitung sisa waktu yang terbuang. Di sinilah, pada Hari Pahlawan, seorang narapidana teroris merenungkan ironi takdirnya. Ia yang pernah menganggap dirinya pejuang, kini dicap sebagai ancaman bagi negara yang sama-sama mengaku mewarisi semangat perjuangan.
Paradoks ini menghadirkan pertanyaan mendasar: Siapakah sesungguhnya yang berhak menyandang gelar pahlawan? Pertanyaan ini menggema di koridor-koridor penjara, tempat di mana batas antara keyakinan dan kesalahan menjadi begitu tipis.
Sejarah Indonesia mencatat, konsep kepahlawanan selalu menjadi arena kontestasi narasi. Soekarno, yang kini diabadikan sebagai pahlawan nasional, pernah pula mendekam dalam penjara kolonial sebagai "pengganggu ketertiban umum". Tan Malaka, dengan visi revolusionernya, bahkan mati di tangan sesama pejuang kemerdekaan. Maka, label "teroris" dan "pahlawan" seringkali bergantung pada siapa yang memegang kendali narasi sejarah.
Para narapidana teroris yang mengaku berjuang atas nama agama dan keadilan, sesungguhnya tengah terjebak dalam paradigma yang keliru. Mereka lupa bahwa Indonesia lahir dari rahim pluralitas, dibesarkan oleh tangan-tangan yang beragam. Founding fathers negeri ini dengan bijak memilih Pancasila sebagai jalan tengah, bukan negara agama maupun negara sekuler murni.
Namun, kesalahan fatal mereka bukanlah pada hasrat untuk membela kebenaran, melainkan pada metode yang mereka pilih. Kekerasan dan teror hanya akan melahirkan lingkaran setan penderitaan, mengkhianati esensi perjuangan sejati yang seharusnya membebaskan, bukan membelenggu.
Di balik jeruji besi, beberapa dari mereka mulai memahami bahwa patriotisme sejati tidak diukur dari kemampuan menghancurkan, tetapi dari kesediaan membangun. Mereka belajar bahwa medan jihad yang sesungguhnya adalah melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan – bukan dengan bom dan peluru, melainkan dengan pendidikan, pemberdayaan, dan dialog.
Program pembinaan yang mereka jalani perlahan membuka mata mereka bahwa NKRI adalah rumah bersama yang harus dijaga, bukan musuh yang harus dihancurkan. Kisah-kisah tentang pahlawan nasional yang mereka pelajari ulang mengajarkan bahwa kepahlawanan sejati terletak pada kemampuan merangkul perbedaan, bukan menghapusnya.
Hari Pahlawan bagi mereka kini menjadi momen introspeksi mendalam. Dari balik terali besi, mereka menyaksikan bagaimana bangsa ini terus bergerak maju, berjuang menghadapi tantangan zaman dengan cara-cara yang lebih bermartabat. Mereka mulai memahami bahwa menjadi pahlawan di era modern tidak lagi soal mengangkat senjata, tetapi tentang mengangkat derajat kemanusiaan.
Perlahan tapi pasti, paradigma kepahlawanan mereka bergeser. Pahlawan sejati adalah mereka yang mampu mengalahkan ego dan dogma sempit dalam dirinya sendiri. Pahlawan adalah mereka yang berani mengakui kesalahan dan memilih jalan rekonsiliasi. Pahlawan adalah mereka yang memahami bahwa keberagaman Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang harus dirawat.
Refleksi ini mengajarkan kita bahwa kepahlawanan bukanlah tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang mampu membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks kekinian, mungkin pahlawan sejati adalah mereka yang berani melawan arus radikalisme dan ekstremisme dengan membawa pesan perdamaian dan persatuan.
Hari Pahlawan, bagi para narapidana teroris yang telah menemukan pencerahan, kini menjadi pengingat akan harga mahal dari sebuah kesalahan paradigma. Namun sekaligus, ini menjadi momentum untuk memulai lembaran baru – menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan menjadi agen perdamaian dan persatuan bangsa.
Maka, dari kegelapan sel tahanan, lahir pencerahan bahwa kepahlawanan sejati tidak diukur dari berapa banyak musuh yang bisa dihancurkan, tetapi dari berapa banyak jembatan perdamaian yang bisa dibangun. Dan mungkin, inilah makna Hari Pahlawan yang paling relevan untuk Indonesia kontemporer.
Kota Pahlawan 10 November 2024
*) A Fida merupakan Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
Panjang naskah maksimal 800 kata
Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
Hak muat redaksi.(*)